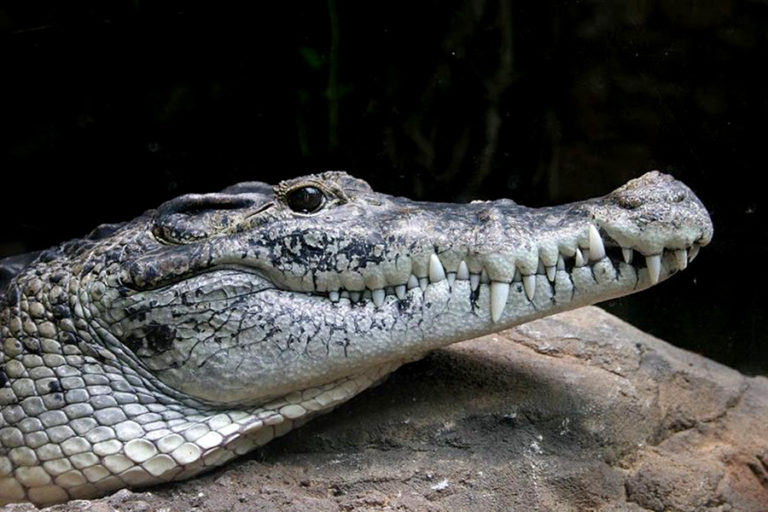Kemenangan Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024 tak datang tanpa ironi. Sosok yang dahulu digambarkan sebagai bagian dari masa lalu kelam Orde Baru, kini sebagian pihak menyebut sebagai pemimpin masa depan. Kemenangannya teraih melalui dukungan penuh dari Joko Widodo, mantan rival yang kini jadi sekutu. Di atas panggung, mereka bersalaman—tetapi di balik layar, yang saling bertukar tangan bukan hanya dukungan politik, juga warisan pembangunan yang sarat kepentingan oligarki.
Asta Cita, dokumen berisi delapan mimpi yang Prabowo gagas, menyimpan janji besar. Dari semua poin itu, salah satu yang perlu disorot adalah ihwal menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Sejak kampanye, Prabowo berulang kali menyebut, Indonesia terlalu kaya untuk menjadi miskin. Sayangnya, dia lupa atau sengaja mengabaikan bahwa tambang yang menggali isi bumi selama puluhan tahun tak pernah membuat rakyat makmur—justru menciptakan kerusakan ekologis, konflik agraria, dan pemiskinan struktural yang panjang.
 Joko Widod, kala itu Presiden Indonesia, bertemu Prabowo Subianto, ketika itu Ketua Umum Partai Gerindra di Beranda Istana Merdeka, Kamis (17/11/16). Pada Prilpres 2024, Prabowo maju sebagai pemenang dan jadi presiden. Foto : Rahmat/setkab.go.id/Mongabay Indonesia
Joko Widod, kala itu Presiden Indonesia, bertemu Prabowo Subianto, ketika itu Ketua Umum Partai Gerindra di Beranda Istana Merdeka, Kamis (17/11/16). Pada Prilpres 2024, Prabowo maju sebagai pemenang dan jadi presiden. Foto : Rahmat/setkab.go.id/Mongabay IndonesiaTanah terampas, kriminalisasi rakyat
Di negeri ini, nyaris tak ada satu pun pulau yang benar-benar terbebas dari tambang. Setiap jengkal tanah yang menyimpan deposit mineral terpetakan, dihitung nilai keuangannya, dan masukkan ke dalam skema besar eksploitasi nasional. Hutan, gunung, pesisir, hingga laut dalamjadi sasaran investasi atas nama pembangunan.
Merujuk catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), hampir 8.000 izin tambang kini tersebar di seluruh penjuru negeri, dengan luas konsesi mencapai lebih 10,4 juta hektar. Angka ini mencerminkan tidak hanya agresivitas ekspansi industri tambang, juga tingkat perampasan ruang hidup yang berlangsung secara sistematis. Izin-izin itu mencaplok lahan pertanian dan perkebunan rakyat, mencemari sumber air dan udara, serta menimbulkan beban ekonomi dan kesehatan yang besar bagi masyarakat sekitar. Tak jarang, kehadiran tambang berujung pada penggusuran paksa kampung-kampung warga.
Tak berhenti di situ, operasi tambang juga berdampak luas pada kawasan hutan. Tambang menjadi salah satu penyumbang utama deforestasi di Indonesia.
Menurut catatan Auriga Nusantara, pada 2024 sekitar 58,7% atau 153.498 hektar kehilangan hutan terjadi di dalam konsesi perusahaan. Rinciannya, mencakup 36.068 hektar di konsesi penebangan (HPH/PBPH HHK-HA), 41.332 hektar kebun kayu (HTI/PBPH HHK-HT), 38.615 hektar di tambang, dan 37.483 hektar konsesi sawit.
Perusakan kawasan hutan ini bukan tanpa konsekuensi. Setiap musim penghujan, kawasan-kawasan yang kehilangan tutupan hutan menjadi rentan terhadap banjir bandang, longsor, dan kerusakan ekosistem. Hutan yang dulu berfungsi sebagai wilayah resapan air kini berubah menjadi lahan terbuka yang tak mampu menahan curah hujan tinggi.
Akibatnya, desa-desa di lereng dan dataran rendah menjadi korban bencana berulang, dan masyarakat terpaksa menanggung dampak dari kebijakan yang memihak industri. Situasi ini, terjadi di hampir seluruh wilayah operasi tambang, mulai dari Halmahera, Morowali, Konawe, hingga Kalimantan Timur.
Ekspansi tambang terus melaju bukan hanya menggerus hutan dan ruang hidup, serta menyebabkan bencana, juga memicu ledakan konflik agraria yang makin tajam.
Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2024 terjadi 295 letusan konflik agraria di berbagai sektor di Indonesia, berdampak pada 67.436 keluarga tersebar di 349 desa. Angka ini meningkat 21% dibanding tahun sebelumnya, mencatat 241 konflik pada 2023.
Dalam konflik itu, sektor pertambangan menyumbang sedikitnya 41 kasus, menyusul sektor perkebunan dan infrastruktur. Konflik-konflik ini tidak berdiri sendiri. Ia hadir bersama represi dan kekerasan struktural.
Selama 2024, sebanyak 556 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi, yang sebagian besar oleh aparat negara dalam konteks pembelaan terhadap korporasi.
Data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menunjukkan, tren mengkhawatirkan. Sejak 2015-2024, sedikitnya 299 orang menjadi korban kriminalisasi karena menolak proyek tambang di wilayah mereka. Angka ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari pola kekerasan struktural lebih luas, di mana negara lebih memilih pendekatan represif ketimbang dialogis dalam merespons kritik dan penolakan warga terhadap proyek-proyek destruktif.
Kriminalisasi terhadap warga yang menolak proyek ekstraktif, misal, tidak terlepas dari peran aktif aparatus keamanan negara baik Polri maupun TNI yang kerap menjadi alat penjaga kepentingan investasi dan pembangunan versi negara. Hukum sejak awal tidak untuk melindungi rakyat, melainkan menjadi alat kekuasaan untuk mematikan resistensi dan melanggengkan dominasi negara-korporasi.
Dalam banyak kasus, polisi dan perusahaan bersekongkol melaporkan serta memproses warga penolak tambang menggunakan berbagai regulasi represif, mulai dari UU Nomor 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Cipta Kerja, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai pasal-pasal karet KUHP.
Bahkan, dalam beberapa kasus ekstrem, mereka gunakan pula instrumen hukum tak lazim, seperti UU Kedaruratan, sebagaimana menimpa Robison Saul, nelayan penolak tambang emas di Pulau Sangihe yang ditangkap dan proses hukum dengan pasal tidak relevan.
Pada titik ini, polisi tampak menjadikan hukum sebagai alat tawar-menawar politik demi melayani kepentingan penguasa dan oligarki, alih-alih bertindak sebagai pelindung masyarakat.
Situasi pelik ini tentu bukan kebetulan, melainkan pola sistematis dan memperlihatkan bagaimana politik, hukum, dan ekstraktivisme beroperasi sebagai satu kesatuan. Setiap proyek ekstraktif selalu menciptakan apa yang Naomi Klein, sebut sebagai sacrifice zones—wilayah-wilayah yang sengaja dikorbankan demi akumulasi keuntungan segelintir elite dan korporasi.
Zona pengorbanan ini kerap kali adalah komunitas adat, desa-desa di pulau kecil, atau wilayah marginal yang jadi ladang tambang, PLTU, smelter, PLTA, kawasan industri, hingga proyek-proyek infrastruktur.
Ekstraktivisme tentu tidak terbatas pada sektor tambang dan migas. Eduardo Gudynas menyebut, ekstraktivisme sebagai model pembangunan yang memprioritaskan pengambilan sumber daya dalam skala besar untuk ekspor, sambil mengabaikan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial.
Di Indonesia, ekstraktivisme tidak hanya menjadi wajah ekonomi, juga cara negara mengorganisasi ruang dan kekuasaan.
 Laut Kabaena, yang tercemar limbah ore nikel. Gaung hilirissi nikel, menyebabkan eksploitasi nikel masif. Foto: Walhi Sultra
Laut Kabaena, yang tercemar limbah ore nikel. Gaung hilirissi nikel, menyebabkan eksploitasi nikel masif. Foto: Walhi SultraKepentingan Prabowo dan kroni
Kepentingan bisnis dan kekuasaan dalam pemerintahan Prabowo Subianto tidak bisa terpisahkan. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo secara terbuka menyatakan, sebagian asetnya “mandek” selama lebih dari dua dekade karena tidak berada di lingkar kekuasaan.
Pernyataan ini menegaskan, kembalinya Prabowo ke posisi strategis—mulai dari Menteri Pertahanan hingga kini Presiden—berkorelasi langsung dengan upaya pemulihan dan perluasan kepentingan bisnis pribadinya.
Kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 juga tidak bisa lepas dari sokongan kuat para oligarki tambang dan elite bisnis yang telah lama menguasai sumber daya alam di Indonesia.
Dia memperoleh dukungan terbuka maupun diam-diam dari sejumlah taipan yang memiliki pengaruh besar, mulai dari Garibaldi “Boy” Thohir, bos Adaro, salah satu raksasa batubara nasional, keluarga Hartono dari Djarum Group, konglomerat yang memiliki kekuatan finansial dan jaringan luas di sektor perbankan, teknologi, dan rokok. Juga, Putera Sampoerna, pewaris imperium Sampoerna Group yang juga memiliki kepentingan di sektor energi dan tembakau.
Tak hanya itu, Prabowo juga dapat sokongan Arini Saraswaty Subianto, putri mendiang taipan Benny Subianto, yang kini mengepalai Persada Capital Investama, perusahaan yang berinvestasi besar-besaran di sektor tambang dan energi.
Selain itu, kabinet besutan Prabowo pun memperlihatkan konsolidasi yang kuat antara politik dan bisnis. Merujuk laporan JATAM, dalam komposisi awal kabinetnya, terdapat 34 dari 48 menteri yang memiliki afiliasi dengan bisnis, baik langsung maupun tidak. Jumlah itu mencerminkan hampir tiga perempat dari total menteri, menunjukkan dominasi kepentingan ekonomi dalam kebijakan pemerintahan. Dari 34 menteri itu, sekitar 15 terhubung dengan sektor ekstraktif, yang menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional.
Beberapa nama yang menonjol dalam hal ini termasuk Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKPM, Roslan Roeslani, mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Erick Thohir, Menteri BUMN, dan Widiyanti Putri Wardhana, istri dari Wisnu Wardhana, pebisnis besar sektor pertambangan.
Nama-nama itu belum mencakup menteri dan wakil menteri yang diduga merupakan “titipan” dari konglomerat atau elite bisnis besar yang selama ini dikenal memiliki kedekatan dengan penguasa dan kekuatan modal.
 Pemilik ulayat di Merauke, Papua Selatan, yang aksi di Jakarta. Mereka khawatir ruang hidup hilang ketika hadir bisnis pangan skala besar lewat food estate cetak sawah di Merauke. Foto: Greenpeace
Pemilik ulayat di Merauke, Papua Selatan, yang aksi di Jakarta. Mereka khawatir ruang hidup hilang ketika hadir bisnis pangan skala besar lewat food estate cetak sawah di Merauke. Foto: GreenpeaceSalah satu nama yang ramai dibicarakan adalah Andi Syamsudin Arsyad, atau lebih dikenal sebagai Haji Isam, taipan batubara dari Kalimantan Selatan juga pemilik PT Jhonlin Group. Haji Isam disebut-sebut memiliki pengaruh signifikan dalam penunjukan pejabat di kabinet, khusus dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan energi dan sumber daya alam.
Komposisi kabinet ini makin menegaskan betapa eratnya hubungan antara pemerintahan dan korporasi dalam menguasai sumber daya alam, yang tidak hanya menguntungkan segelintir elite juga memperkuat dominasi bisnis ekstraktif dalam kebijakan publik Indonesia.
Persekongkolan ini menunjukkan bagaimana kontestasi elektoral di Indonesia telah bergeser jauh dari sekadar perdebatan ide dan program kerja. Ia kini menjelma menjadi ajang konsolidasi modal dan kuasa, di mana sektor-sektor ekonomi strategis, terutama pertambangan, menjadi medan rebutan utama elite politik dan oligarki.
Dalam konteks ini, Jeffrey Winters dalam bukunya Oligarchy (2011) menyebut, oligarki bukan sekadar soal kepemilikan kekayaan, tetapi tentang kekuasaan untuk melindungi kekayaan itu melalui kontrol atas negara. Pemilu, menurut Winters, menjadi satu mekanisme penting bagi oligarki untuk memastikan bahwa negara tetap bekerja untuk melayani dan menjaga kepentingan mereka.
Sejalan juga dengan analisis Richard Robison dan Vedi R. Hadiz dalam Reorganising Power in Indonesia (2004), yang menyatakan, pasca-Orde Baru, demokrasi di Indonesia bukannya membubarkan oligarki lama, melainkan membuka jalan bagi konsolidasi baru antara elite politik dan elite bisnis.
Dalam konteks ini, sektor tambang—karena karakteristiknya yang padat modal, padat teknologi, berisiko tinggi, namun sangat menguntungkan—menjadi simpul strategis di mana kepentingan bisnis dan kekuasaan saling terhubung secara erat.
 Lahan sudah dibersihkan untuk cetak sawah food estate di Merauke, Papua. Foto: Yayasan Pusaka
Lahan sudah dibersihkan untuk cetak sawah food estate di Merauke, Papua. Foto: Yayasan PusakaApi perlawanan
Dalam situasi ini, tak ada oposisi sejati yang tampil untuk membela rakyat. Mayoritas partai politik sibuk bertengkar dengan kepentingannya sendiri, bahkan justru terlibat dalam transaksi kuasa atas sumber daya alam.
Jeffrey Winters mengingatkan, kekuasaan oligarkis bertahan bukan semata karena kekayaan, tetapi karena kemampuan membentuk dan mengendalikan institusi politik. Negara tak netral, melainkan menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa kekayaan alam terus tereksploitasi tanpa hambatan sosial-politik.
Oposisi terhadap tambang—ketika tak hadir di ruang formal—harus dibangun dari bawah, dari kampung-kampung yang terrampas, dari sungai-sungai yang tercemar, dari tubuh-tubuh yang ditahan tanpa sebab.
Maka, terus nyalakan bara perlawanan karena di tengah ketiadaan keberpihakan elit, rakyat tak punya pilihan lain selain bertahan.
Perlawanan terhadap ekstraktivisme adalah perlawanan untuk hidup, untuk air bersih, untuk ruang hidup yang adil dan lestari. Karena negara absen, maka warga-lah yang harus membentuk bentengnya sendiri.
Perlawanan warga terhadap tambang bukan sekadar soal konflik lokal, juga bagian dari upaya menyelamatkan masa depan ekologis bangsa. Karena seperti dikatakan David Harvey, bentuk-bentuk baru akumulasi kapital selalu menciptakan “accumulation by dispossession”—perampasan hak dan ruang hidup untuk keuntungan segelintir.
 Aksi warga Kawasi, Pulau Obi. Halmahera Selatan. Foto: Dokumen warga.
Aksi warga Kawasi, Pulau Obi. Halmahera Selatan. Foto: Dokumen warga.Di tengah langit demokrasi yang mendung, dan Prabowo yang sibuk dengan politiknya sendiri, harapan tidak boleh padam. Perlawanan dari komunitas yang terpinggirkan adalah bentuk tertinggi dari demokrasi yang hidup. Ia menolak tunduk, menolak dilupakan.
Sebagaimana dikatakan Naomi Klein dalam This Changes Everything (2014), perjuangan melawan ekstraktivisme adalah perjuangan untuk masa depan bersama—masa depan yang tidak bisa dibangun di atas kehancuran ekologi dan penderitaan manusia.
Kalau negara dan pasar telah berpihak pada tambang, maka suara rakyat dari kampung-kampunglah yang harus kita dengarkan dan bela.
 Pembuatan kanal dan pembukaan hutan untuk periapan kebun sawit di Riau. Ekspansi sawit yang berisiko membabat hutan dan lahan gambut bukan mustahil terjadi di tengah program pangan dan energi saat ini. Foto: Suryadi/Mongabay Indonesia
Pembuatan kanal dan pembukaan hutan untuk periapan kebun sawit di Riau. Ekspansi sawit yang berisiko membabat hutan dan lahan gambut bukan mustahil terjadi di tengah program pangan dan energi saat ini. Foto: Suryadi/Mongabay Indonesia*******
*Penulis adalah Melky Nahar, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Tulisan ini merupakan opini penulis.

 13 hours ago
4
13 hours ago
4