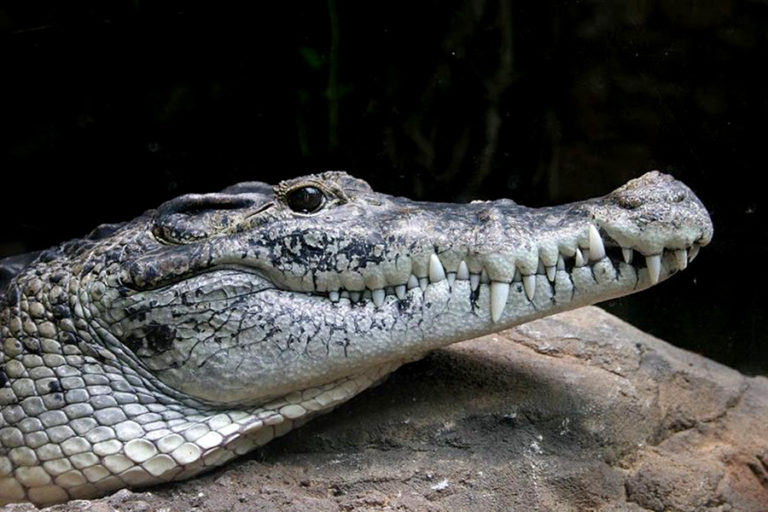- Rencana pemerintah menjadikan gas alam sebagai energi transisi utama sebelum energi terbarukan salah kaprah. Laporan terbaru Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Greenpeace Indonesia menyebut, rencana itu akan berdampak negatif bagi lingkungan, sosial dan ekonomi.
- Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, justru menilai rencana penambahan pembangkit gas 22 GW akan lemahkan transisi energi maupun upaya atasi krisis iklim. Soalnya, metana (CH4), senyawa yang dihasilkan dari pemanfaatan gas alam, punya efek pemanasan 80 kali lebih kuat daripada CO2 selama 20 tahun dan 28 kali lebih kuat dalam rentang 100 tahun.
- Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menyebut, melonjaknya beban subsidi dan kompensasi untuk sektor energi akan menekan APBN. Di sisa tahun 2025, contoh, pemerintah punya waktu sembilan bulan untuk lunasi utang jatuh tempo yang mencapai Rp800,33 triliun. Nominal setiap bulannya bervariasi, namun mencapai puncak di bulan Juni 2025 yakni senilai Rp178,9 triliun.
- Putu Indy Gardian, Technical Spesialist Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia, menilai, pemanfaatan gas sebagai energi transisi merupakan keniscayaan. Sebab, transisi langsung dari batubara pada energi terbarukan akan menimbulkan efek kejut yang terlalu besar bagi finansial maupun ketersediaan energi.
Rencana pemerintah menjadikan gas alam sebagai energi transisi utama sebelum energi terbarukan salah kaprah. Laporan terbaru Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Greenpeace Indonesia menyebut, rencana itu akan berdampak negatif bagi lingkungan, sosial dan ekonomi.
Berdasarkan draf Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2033, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 102 GW hingga 2040, dengan komposisi 75% energi terbarukan dan 20% gas (22 GW).
Rencana itu menempatkan gas sebagai tahapan transisi energi sebelum beralih ke energi terbarukan. Soalnya, pemerintah menilai, potensi gas alam di Indonesia cukup besar, bisa memastikan pasokan energi yang andal, lebih ramah lingkungan serta berpeluang kurangi impor, khusus liquified petroleum gas (LPG).
Catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Indonesia punya potensi gas alam, dengan cadangan terbukti 41,62 triliun cubic feet (TcF) dan 68 cekungan potensial yang belum tereksplorasi. Mereka memperkirakan ada surplus gas hingga 1.715 juta kaki kubik standar per hari/ million Standar cubic feet per day (MMSCFD) dalam 10 tahun ke depan.
Optimisme meninggi, karena hingga 2024, KESDM mencatat produksi gas alam Indonesia 6.635 MMSCFD, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Rencananya, sepanjang 2027-2028, pemerintah masih akan tingkatkan produksi gas alam melalui sejumlah proyek strategis.
Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, menilai rencana penambahan pembangkit gas 22 GW akan lemahkan transisi energi maupun upaya atasi krisis iklim. Soalnya, metana (CH4), senyawa dari pemanfaatan gas alam, punya efek pemanasan 80 kali lebih kuat daripada CO2 selama 20 tahun dan 28 kali lebih kuat dalam rentang 100 tahun.
Emisi metana juga terbesar setelah CO2, dengan kontribusi sebesar 30% pemanasan global sejak masa pra-industri, dan sebabkan lebih dari 1 juta kematian dini tiap tahun.
“Secara persepsi, gas alam lebih positif, lebih bersih dari energi fosil lainnya dan kurang serius dampaknya. Tetapi, gas alam (senyawa) utamanya adalah metana yang sangat problematik, karena emisi gas rumah kaca yang serius,” katanya dalam peluncuran laporan kolaborasi itu, di Jakarta, Kamis (24/4/25).
Baginya, rencana pengembangan 22 GW pembangkit gas hanya akan menghalangi komitmen iklim dan target peningkatan energi terbarukan yang pemerintah sampaikan di forum-forum internasional.
Ketika hadiri KTT G20, misal, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan capai net zero emission pada 2050. Kemudian, Utusan Khusus Presiden di Conference of the Parties (COP) Baku, Hashim Djojohadikusumo bilang, hingga 2040 Indonesia siap tingkatkan bauran energi terbarukan 75 GW.
“Pernyataan ini harus dicatat sebagai pernyataan pemerintah. Tetapi kalau kita lihat perkembangan sekarang, terutama dengan gas sebagai energi transisi utama, pernyataan ini akan sangat sulit dipenuhi.”
Seharusnya, upaya transisi energi beriringan dengan komitmen dekarbonisasi. Hal itu seturut dengan penilaian International Energy Agency (IEA), yang merekomendasikan pengurangan emisi metana sebesar 75% tahun 2030 untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat celsius.
Selain itu, gas alam merupakan energi yang tidak terbarukan. Karena itu, pengembangan 22 GW pembangkit gas hingga 2040, akan menempatkan Indonesia sebagai negara importir, seperti halnya yang terjadi pada minyak sejak 2004.
Dia perkirakan, status pengimpor akan berlaku sejak 2040 dan menjadi net importer pada tahun 2050, dengan 30% kebutuhan gas didatangkan dari negara lain. “Kalau pada tahun 2050 masih andalkan impor minyak pada jumlah signifikan, akan bertambah juga dengan impor gas,” ujar Leonard.
 Grati Power Generation and O&M Services Unit (POMU) berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur. Grati POMU mengelola 2 sub unit yaitu Perak & Grati yang mengoperasikan Pusat Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU) dan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan total kapasitas terpasang sebesar 764 MW. Foto : Indonesia Power
Grati Power Generation and O&M Services Unit (POMU) berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur. Grati POMU mengelola 2 sub unit yaitu Perak & Grati yang mengoperasikan Pusat Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU) dan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan total kapasitas terpasang sebesar 764 MW. Foto : Indonesia PowerKerugian ekonomi
Kajian kolaborasi itu menyebut, pengembangan dan operasional pembangkit gas 22 GW akan menambah beban keuangan negara. Pasalnya, lewat harga gas bumi tertentu (HGBT), pemerintah sudah batasi harga gas untuk pembangkit listrik di angka US$6 per Metric Million British Termal Unit (MMBTU). Sementara, harga pasar domestik mencapai US$10 MMBTU. Itu berarti, pemerintah harus menyubsidi US$4 MMBTU.
Sebelumnya, kalkulasi Yayasan Indonesia Cerah, 20 GW pembangkit listrik bakal perlu bahan bakar gas sekitar 4.640.000 MMBTU per hari. Artinya, pada setiap selisih harga gas US$1, pemerintah harus tanggung US$4,64 juta atau Rp74,24 miliar setiap hari (Rp26,7 triliun per tahun).
Makin besar selisih harga gas dengan HGBT, makin besar pula potongan pendapatan negara dari sektor migas.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menyebut, melonjaknya beban subsidi dan kompensasi untuk sektor energi akan menekan APBN. Di sisa tahun 2025, contoh, pemerintah punya waktu sembilan bulan untuk lunasi utang jatuh tempo yang mencapai Rp800,33 triliun. Nominal setiap bulan bervariasi, namun mencapai puncak pada Juni 2025 senilai Rp178,9 triliun.
“Jadi, kalau PLN minta kompensasi terus ke APBN, semua akan terlihat pada beban utang jatuh tempo, yang sampai 2034 akan mengalami tekanan. Indonesia, sebagai informasi, bunga utangnya sudah 7% untuk tenor 10 tahun. Jadi pemerintah harus hitung juga tambah pembangkit gas 22 GW, bunga utangnya berapa,” katanya.
Kajian kolaborasi ini menyebut, pemanfaatan teknologi turbin gas sebagai pembangkit tenaga listrik merugikan output ekonomi Rp941,4 triliun secara kumulatif, hingga 2040. Sementara, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) siklus gabungan menurunkan output hingga Rp280,9 triliun.
Ekspansi pembangkit gas juga akan menambah beban biaya kesehatan. Dengan tambahan 22 GW pada 2040, beban risiko klaim BPJS kesehatan diproyeksikan mencapai Rp1.545,9 triliun hingga Rp1.705,9 triliun.
Selain itu, defisit transaksi di sektor minyak dan gas akan berdampak pelemahan nilai tukar rupiah. Karena, kata Bhima, importasi gas pada tahun 2040 akan diikuti meningkatnya kebutuhan valuta asing.
“Ini masalah ketahanan ekonomi nasional. Kita sudah terjebak sekian lama oleh fluktuasi batubara, minyak mentah, ke depan ditambah fluktuasi gas.”
Dia menilai, transisi melalui pemanfaatan gas alam merupakan jebakan yang akan hambat pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Sebab, ambisi capai 75% bauran energi di tahun 2040, terancam biaya investasi dan dukungan kebijakan untuk pembangkit gas.
Begitu pula dengan target dekarbonisasi. Kajian ini perkirakan, operasi pembangkit gas 22 GW hasilkan lonjakan CO2 hingga 49,02 juta ton per tahun dan metana hingga 43.769 ton pertahun.
“Kok kecil ya (kontribusi metana)? Tapi seperti disebutkan tadi, metana 86 kali lebih berbahaya dibanding CO2.”
Secara sosial, katanya, pembangkit turbin gas berisiko turunkan serapan tenaga kerja hingga 6,7 juta orang pada 2040. Angka ini berasal dari gangguan pendapatan masyarakat di sektor terdampak, seperti kelautan dan perikanan.
Dia contohkan, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Karawang sebabkan terganggunya aktivitas pencarian ikan nelayan. Karena, umumnya, lokasi pembangkit gas berada di daerah pesisir. Sementara pembangkit offshore (lepas pantai) berada di tengah laut.
“Gas itu mulai dari eksplorasi-eksploitasi itu timbulkan skenario konflik dari segi tata ruang, konflik lahan dengan masyarakat. Nelayan kena, ekosistem juga kena,” ujar Bhma.
 Pembangkit panas bumi Sorik Marapi, Januari lalu gas beracun bocor, kini alami kebakaran. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia
Pembangkit panas bumi Sorik Marapi, Januari lalu gas beracun bocor, kini alami kebakaran. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay IndonesiaSebuah keniscayaan
Putu Indy Gardian, Technical Spesialist Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia, menilai, pemanfaatan gas sebagai energi transisi merupakan keniscayaan. Sebab, transisi langsung dari batubara pada energi terbarukan akan menimbulkan efek kejut yang terlalu besar bagi finansial maupun ketersediaan energi.
Bagi dia, transisi energi berkeadilan harus perhatikan aspek 4A dalam indeks ketahanan energi, yakni availability (ketersediaan), affordability (keterjangkauan), accessibility (bisa diakses) dan acceptability (penerimaan).
Dari sisi penerimaan, rencana penggunaan energi gas telah pertimbangkan dampak lingkungan. Berdasarkan indikator pemanasan global, katanya, emisi yang dihasilkan gas 55% lebih rendah dibanding batubara. Kemudian, PLTG hasilkan PM10 yang 100 kali lebih rendah polusi PLTU batubara.
“Kalau kita bandingkan, gas memang lebih ramah lingkungan kalau dibanding batubara,” katanya, menanggapi laporan itu.
Ketimbang energi terbarukan, pembangkit gas punya fleksibilitas tinggi, keandalan sistem dan jamin kestabilan listrik. Sementara, energi terbarukan bersifat intermiten atau tidak tetap karena sejumlah faktor, salah satunya cuaca.
Sisi lain, menjadikan energi terbarukan sebagai pembangkit baseload yang beroperasi dalam waktu lama, perlu biaya mahal. Misal, penggunaan baterai akan tingkatkan biaya operasional dua kali lipat, dengan risiko harga komoditas fluktuatif. Kemudian, berdasarkan ketersediaannya, energi terbarukan tersebar di lokasi spesifik yang berpotensi tingkatkan biaya transmisi dan distribusi dari satu daerah ke daerah lain.
Berbeda tentang kekhawatiran Indonesia jadi pengimpor gas di masa mendatang, Putu justru bilang, suplai gas untuk kebutuhan dalam negeri akan aman hingga 2050. Mengacu pada pemodelan ketika merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Sementara, masa operasional PLTG yang sekitar 25-30 tahun disebut telah sesuai dengan proyeksi transisi energi. “Jadi ketika gasnya habis, itu saat (operasional) PLTG-nya habis.”

*****
Kajian Ingatkan Proyek Gas Alam Hambat Dekarbonisasi Indonesia

 1 day ago
9
1 day ago
9