- Krisis iklim mengancam kosakata (leksikon) lokal orang Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Hal ini dipicu dari makin sulitnya tanaman lokal penyusun uma bokolo (rumah besar). seperti pohon kadimbil (merbau sumba), kahikara (tali hutan), hingga linyo (lino)
- Paulina Maria Yovita Kosat, penulis ensiklopedia ‘Kembaliku ke Uma Bokolo’, menyebut generasi muda tidak mengetahui arti beberapa leksikon material alam dan pendirian uma bokolo, lisan maupun tulisan.
- Iklim NTT yang makin kering membuat tanaman-tanaman tersebut susah ditemukan. BMKG mencatat ada anomali perbedaan curah hujan yang signifikan di NTT tahun 2024.
- Erwin Fajar Hasrianda, Peneliti dari Pusat Riset Botani Terapan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), saat dihubungi, menjelaskan, tumbuhan butuh air dan suhu lingkungan dalam rentang yang berbeda-beda untuk bisa bertahan hidup. Namun, kemarau berkepanjangan dan pemanasan global menyebabkan ketersediaan air tumbuhan berkurang.
“Satu tumbuhan yang tidak tumbuh, menyumbang kepunahan beberapa leksikon (kosakata) bahasa daerah Kodi.” Paulina Maria Yovita Kosat, penulis ensiklopedia ‘Kembaliku ke Uma Bokolo’, mengucapkan wejangan itu.
Mengacu pada isi bukunya yang menggambarkan hubungan erat antara lingkungan dan budaya di Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Buku itu berisi leksikon pendirian uma bokolo atau ‘rumah besar’. Disusun secara ilmiah dan terjabarkan dalam perspektif Orang Kodi. Menggambarkan kata-kata yang hampir punah, krisis iklim jadi salah satu pemicu.
Jovin, sapaan karibnya, memandang uma bokolo bukan sekadar bangunan. Struktur yang menggunakan material lokal ini tempat lahirnya kabisu (suku) dalam keluarga besar, tempat pertama kebudayaan bertumbuh.
Berbagai ritual adat Kodi pun dilakukan di sini. Bangunan yang menggunakan pohon kadimbil (merbau sumba) sebagai bahan utamanya ini merupakan sentra kebudayaan.
Dalam bukunya, Jovin menjelaskan tiang utama uma bokolo terdiri dari empat batang, lalu delapan batang lawiri kopa (tiang/balok bantu). Tiang-tiang ini juga menggunakan pohon kadimbil. Batang pohon linyo (lino) atau batang pohon besi (johar) bisa jadi alternatif.
Penggunaan pohon kadimbil sendiri karena warna yang khas, tingkat kekerasan yang tinggi, awet, tahan jamur dan rayap, serta tidak mudah susut jika diolah dengan proses pengeringan.
Selain itu, ada pula kahikara (tali hutan) yang dikeringkan untuk mengikat lawiri dan onghol (bambu). Kahikara memiliki tekstur kuat, berserat, awet, dan tidak susut. Selanjutnya ada paneta (rotan), punghe ngiyo (kelapa), dan punghe labba (pinang).
Leksikon-leksikon penyusun uma bokolo ini terancam hilang karena kini sulit diperoleh. Pola hujan yang tidak menentu menyebabkan kadimbil sulit hidup ketika ditanam.
Padahal, pohon ini termasuk tahan panas. Namun, proses awal pertumbuhannya membutuhkan banyak air. Kurangnya curah hujan dan musim kemarau berkepanjangan membuatnya sulit bertahan hidup.
Jovin bilang, kahikara dan linyo sulit ditemukan di Pulau Sumba. Kahikara, misal, hanya berada di kawasan hutan lindung Tana Ndaru di Sumba Tengah.
Pemerintah sukar memberikan akses masuk hingga masyarakat tidak lagi leluasa menebang pohon. Sedangkan masyarakat harus mencari linyo hingga ke Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur.
Perilaku manusia juga jadi memicu kelangkaan bahan alam penyusun uma bokolo, seperti yang menimpa alang-alang (ngingo). Banyaknya warga membuka lahan pertanian dengan menyemprot obat rumput memengaruhi kesuburan tanah tempat ngingo tumbuh.
Sebagian warga bahkan ada yang sengaja menyemprotkan bahan kimia ini supaya ngingo bisa panen sebelum waktunya demi mendapat keuntungan kilat.
Padahal, Masyarakat Adat Kodi menggunakan ngingo sebagai atap, pelindung dari sinar matahari, hujan, dan angin. Umumnya, warga memanen tumbuhan ini di hutan atau di padang.
Kelangkaan material-material alam ini juga menjadi masalah baru. Pasalnya, harganya turut melonjak.
Pohon kadimbil yang telah ditebang dan dikupas kulitnya berkisar antara Rp35 juta-Rp45 juta per batang. Itu berarti, satu uma bokolo yang membutuhkan empat batang tiang bisa merogoh kocek hingga Rp180 juta.
Jika tidak ada uang untuk membeli, maka masyarakat harus barter. Satu batang pohon kadimbil biasa ditukar dengan satu kerbau, kuda, atau babi. Harga kerbau pun kini berkisar antara Rp10 juta hingga Rp14 juta per ekor.
Langka dan mahalnya material alam ini juga memicu penggunaan material modern untuk uma bokolo. Jovin bilang, beberapa bangunan saat ini ada yang menggunakan seng, tiang beton, semen, hingga paku. Pengerjaannya pun ada yang menggunakan alat modern.
Sebagian Masyarakat Adat Kodi pun belum bisa membangun uma bokolo. Sebagian rumah adat tersisa tiang karena kesulitan mendapat material alam.
Keterbatasan ini juga membuat generasi muda Kodi sulit merekam leksikon material penyusun uma bokolo. Mereka pun tidak mengetahui fisik dari beberapa material alam itu.
Kondisi ini makin parah dengan terancam hilangnya upacara adat dan ungkapan yang berkaitan dengan ritual pendirian rumah ini.
“Dampaknya sudah dirasakan masyarakat sejak 10 atau 20 tahun yang lalu, tapi masih kurang masif dibicarakan di kalangan masyarakat umum dan pemerintah,” kata dosen muda dari Universitas Nusa Cendana Kupang ini.
 Rumah Adat di Kampung Tohik, Desa Wura Homba, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Rumah adat atau rumah besar (uma bokolo) ini sepenuhnya terbuat dari material alam atau pohon-pohon lokal yang ada di daerah tersebut. Foto Jovin Kosat
Rumah Adat di Kampung Tohik, Desa Wura Homba, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Rumah adat atau rumah besar (uma bokolo) ini sepenuhnya terbuat dari material alam atau pohon-pohon lokal yang ada di daerah tersebut. Foto Jovin KosatAncaman kepunahan tumbuhan
Erwin Fajar Hasrianda, Peneliti dari Pusat Riset Botani Terapan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjelaskan, tumbuhan butuh air dan suhu lingkungan dalam rentang yang berbeda-beda untuk bisa bertahan hidup. Namun, kemarau berkepanjangan dan pemanasan global menyebabkan ketersediaan air tumbuhan berkurang.
Beberapa tanaman, katanya, memiliki adaptasi untuk dorman (istirahat) saat lingkungan terlalu kering, atau mengurangi tingkat metabolisme saat lingkungan tidak menguntungkan. Pada masa itu, tanaman cukup mengonsumsi cadangan nutrisi yang mereka simpan sebelumnya.
Tumbuhan pun beradaptasi dengan menurunkan peluang kehilangan air, seperti pembukaan stomata yang lebih minim, daun yang lebih kecil, atau pemanjangan akar agar bisa memperoleh cukup air dari lingkungannya. Kalau kondisi ini terjadi lebih panjang dari periode biasanya, maka ia berisiko tinggi kehabisan cadangan makanan dan mati, semisal layu permanen.
Tahun 2024, katanya, ada pergeseran pola hujan dari yang sebelumnya terjadi awal September atau Oktober, menjadi Desember, di sebagian wilayah Indonesia. Kondisi ini, mengganggu pertumbuhan tanaman yang beradaptasi dengan pola enam bulan iklim kering (kemarau), dan enam bulan basah (penghujan).
Suhu kering dan cuaca panas dalam waktu lama membuat tumbuhan sulit bertahan. Karena mereka kehabisan cadangan air dan nutrisi.
“Ketika lebih dari enam bulan atau satu tahun itu kekeringan, tentu tanaman agak kesulitan untuk bertahan, karena selama ini dari pola adaptasinya adalah untuk bertahan di tidak lebih dari enam bulan musim kering itu, atau tidak untuk setahun.”
Senada dengan Buku The State of Climate BMKG di NTT tahun 2024. Yang mencatat beberapa wilayah di NTT mengalami peningkatan yang mencolok dibanding rata-rata suhu dalam tiga dekade terakhir. Menurut BMKG, perubahan itu indikasi penting dalam memahami dampak perubahan iklim yang makin terasa di wilayah NTT.
Dari sisi curah hujan, misal, pola hujan di NTT menunjukkan perbedaan signifikan antara musim hujan dan kemarau. Awal 2024, sebagian besar NTT mengalami curah hujan bervariasi. Beberapa normal hingga di atas normal, puncaknya pada maret.
Curah hujan mulai menurun seiring dengan peralihan musim hujan ke musim kemarau, April 2024. Bulan Mei, Juni, dan Juli, sebagian besar NTT mengalami curah hujan di bawah normal atau cenderung lebih kering.
Puncak kemarau 2024 terjadi pada Agustus. Catatan BMKG, hampir seluruh wilayah NTT mengalami curah hujan jauh di bawah normal, beberapa bahkan kering ekstrem. Angin monsun timur yang bertiup dari Australia membawa udara kering, sehingga curah hujan minim.
Secara umum, BMKG mencatat daerah dengan curah hujan rendah atau kurang dari 1.000 mm pada tahun 2024 tersebar di bagian barat Pulau Sumba, Alor, dan beberapa daerah di Timor. Sedangkan wilayah dengan curah hujan tinggi tersebar di bagian tengah Pulau Flores.
Kesimpulan BMKG, El Nino dan La Nina yang menyebabkan ketidakstabilan pola hujan di tahun 2024 jadi faktor pemicu anomali iklim yang signifikan di NTT.
 Pohon kandimbil di Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT yang digunakan sebagai material utama untuk membangun uma bokolo atau rumah adat masyarakat Kodi. Foto: Jovin Kosat.
Pohon kandimbil di Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT yang digunakan sebagai material utama untuk membangun uma bokolo atau rumah adat masyarakat Kodi. Foto: Jovin Kosat.***
Dalam bukunya, Jovin menilai banyak generasi muda tidak mengetahui arti beberapa leksikon material alam dan pendirian uma bokolo, lisan maupun tulisan. Perkembangan teknologi memengaruhi mereka menggunakan bahasa sekuler ketimbang lokal atau bahasa Kodi.
Pembukaan lahan pertanian yang tidak tepat prosedur juga menyebabkan material alami penyusun uma bokolo sulit tumbuh. Misalnya penebangan pohon tanpa penanaman kembali, penyemprotan bahan kimia, hingga pembakaran hutan.
Padahal, katanya, tiap bagian tumbuhan menyumbang leksikon bahasa lokal. Karena itu perlu upaya lebih kuat untuk melestarikan leksikon bahasa Kodi. Tidak sekadar lewat anjuran atau nasihat, semua harus mulai dari uma bokolo.
“Jika tumbuhan ini hilang, material untuk mendirikan uma bokolo tidak ada, artinya uma bokolo tidak bisa dibangun.”
Keresahan itu mendorongnya berkoordinasi dengan beberapa pihak, antara lain, Kementerian Kebudayaan maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Niat baiknya direspons dengan dukungan 900 anakan pohon kadimbil dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina. Ia pun menyalurkan anakan tersebut kepada masyarakat Kodi.
Perempuan asli Kodi itu pun merasa bangga mampu mengucapkan bahasa ibu itu hingga dewasa. Kehadiran ensiklopedia 109 halaman yang mendapatkan dukungan penuh dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) dan Dana Indonesia ini merupakan langkah awal untuk terus mengedukasi anak muda tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan budaya melalui bahasa daerah Kodi.
Dia berharap, bukunya bisa mengajak generasi muda Kodi untuk mengetahui leksikon pendirian uma bokolo, mempelajari dan memaknai adat istiadat, dan mencintai kembali kebudayaan mereka. Juga, menjadi pengantar bagi materi muatan lokal untuk bahasa daerah Kodi.
Ensiklopedia ini juga nantinya bisa didistribusikan ke sekolah-sekolah lain di seluruh Sumba Barat Daya.
“Ke depan saya sudah dikontak oleh Kantor Bahasa untuk membuat kamus bahasa Kodi.”
*****

 4 days ago
14
4 days ago
14









![Ironi Penguatan Pangan Kala Lahan Petani Terus Tergusur [2]](https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2025/04/desa-Iwul-4-768x512.jpg)





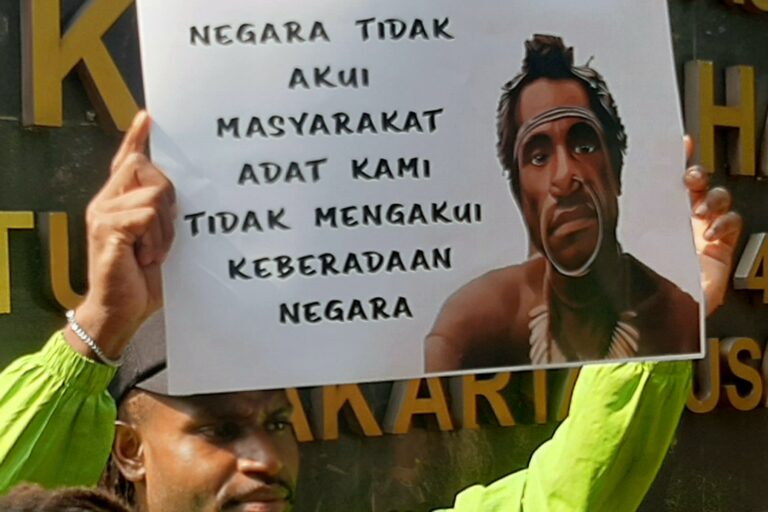



![Protes Penggusuran, Warga Desa Iwul Tanam Pohon [1]](https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2025/04/Foto-dari-Achmad-Rizki-Muazam-3-768x512.jpg)

























