- Sampah dapat diolah menjadi energi? Teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF) memungkinkan sampah yang telah diproses digunakan sebagai bahan bakar untuk pabrik semen.
- Abdul Ghofar, Juru Kampanye Polusi dan Keadilan Iklim Perkotaan Walhi Nasional, mengatakan proyek PLTSa yang dijalankan sejak 2007 justru menimbulkan lebih banyak masalah dibandingkan solusi.
- Nindhita Proboretno, Toxics Program Manager Nexus3 Foundation, mengungkapkan seperti halnya RDF, PLTSa bukanlah solusi utama permasalahan sampah. Justru, potensi persoalan baru yang lebih besar.
- Problem utama PLTSa di Indonesia adalah tingginya presentase sampah basah, sekitar 60-70 persen dari total sampah domestik. Kalau dibakar, butuh energi besar untuk mengeringkannya.
Apakah sampah bisa diolah menjadi energi?
Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, menyatakan, pengelolaan sampah telah mengalami kemajuan. Teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF) mulai diterapkan, memungkinkan sampah yang telah diproses digunakan sebagai bahan bakar untuk pabrik semen.
“RDF mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Sebagian sampah disuplai ke pabrik semen, sebagian lagi diolah menjadi batu bata,” terangnya, dalam kunjungannya ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Rabu (19/3/2025).
Dia menjelaskan, fasilitas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mampu kelola 100 ton sampah per hari, serta proyek RDF di Rorotan, Jakarta, mampu kelola sampah 2.500 ton per hari. Namun, implementasi teknologi ini masih terganjal regulasi.
Salah satunya, skema tipping fee, yaitu biaya yang dibayarkan pemerintah kepada perusahaan pengolah sampah untuk setiap ton sampah yang diproses.
Selain itu, regulasi terkait harga listrik dari pembangit sampah juga masih menjadi perdebatan.
“Harga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dinilai terlalu rendah, sehingga kurang menarik investor,” jelasnya.
Baca: Benahi Tata Kelola Sampah Nasional
 Begini kondisi sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. Foto: Falahi Mubarok/Mongabay Indonesia
Begini kondisi sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. Foto: Falahi Mubarok/Mongabay IndonesiaHarga jadi kendala
Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, mengatakan skema harga listrik yang berlaku masih jadi kendala pembangunan insinerator. Selama 10 tahun terakhir, harga listrik dari PLTSa berkisar Rp8-13.500 per kWh.
“Kalau harganya bisa disesuaikan antara pemerintah pusat dan daerah, saya yakin ini akan menjadi solusi yang lebih baik.”
Selama ini, katanya, karena harga listrik belum sesuai, banyak yang memilih membangun RDF karena lebih mudah dan ada pembelinya, yaitu industri semen. Harga listrik ideal bagi investor sekitar Rp16-20 ribu per kWh.
“Tantangannya, regulasi bisa mendukung pengembangan energi dari sampah.”
Praktikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), mengatakan permasalahan sampah memiliki dampak luas, terutama aspek kesehatan dan bencana. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, namun koordinasi lintas sektor.
“Penanganan harus menyeluruh, dimulai dari hulu di Kemenko Pangan yang juga membawahi urusan lingkungan, tata ruang, dan pengelolaan lahan. Sehingga, risiko bencana bisa diminimalisir.”
Baca: Kajian Sebut Risiko Pembangkit Listrik Sampah
 Sampah masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Foto: Falahi Mubarok/Mongabay Indonesia
Sampah masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Foto: Falahi Mubarok/Mongabay IndonesiaTidak efisien
Abdul Ghofar, Juru Kampanye Polusi dan Keadilan Iklim Perkotaan Walhi Nasional, mengatakan proyek PLTSa yang dijalankan sejak 2007 justru menimbulkan lebih banyak masalah dibandingkan solusi.
Pada 2016, proyek ini resmi masuk Proyek Strategis Nasional (PSN), diperkuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018, yang menargetkan pembangunan PLTSa di 12 kota besar di Indonesia.
Walhi sempat mengajukan judicial review kebijakan ini. Mahkamah Agung memutuskan pembangunan PLTSa melanggar peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
“Namun, pemerintah tetap melanjutkan dengan berbagai revisi regulasi,” ungkapnya, Kamis (20/3/2025)
Saat ini, hanya dua PLTSa yang beroperasi, yakni di Surakarta dan Surabaya. Namun, keduanya dinilai gagal mencapai target. Di Surakarta, efektivitas operasional hanya 4 persen, sedangkan di Surabaya sekitar 30-40 persen.
“Pemerintah mengakui dalam berbagai presentasi bahwa kedua PLTSa tersebut tidak mampu menangani volume sampah yang dijanjikan. Produksi listriknya jauh dari target,” jelas Gofar.
Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2020 menunjukkan, skema pembiayaan PLTSa berisiko besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap ton sampah yang dibakar dikenakan tipping fee sekitar Rp500 ribu.
“Ironis, pemerintah justru berencana membangun PLTSa hingga 30 kota.”
Walhi juga menyoroti RDF yang mempunyai dampak lingkungan.
“Di Rorotan, dampak negatif langsung dirasakan warga, seperti bau menyengat, polusi udara, dan peningkatan kasus ISPA.”
 Begini penampakan truk pengangkut sampah yang menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. Foto: Falahi Mubarok/Mongabay Indonesia
Begini penampakan truk pengangkut sampah yang menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. Foto: Falahi Mubarok/Mongabay IndonesiaBukan solusi utama
Nindhita Proboretno, Toxics Program Manager Nexus3 Foundation, mengungkapkan seperti halnya RDF, PLTSa bukanlah solusi utama permasalahan sampah. Justru, potensi persoalan baru yang lebih besar.
Problem utama PLTSa di Indonesia adalah tingginya presentase sampah basah, sekitar 60-70 persen dari total sampah domestik.
“Kalau dibakar, butuh energi besar untuk mengeringkan.”
Hasil emisi juga berbahaya, seperti dioksin dan furan yang dapat mencemari udara dan membahayakan kesehatan manusia. Ini merujuk hasil kajian di 9 lokasi di Jawa Barat, Bali dan NTB.
Sampel dari Bantar Gebang mengandung senyawa polutan organik persisten (POPs) seperti PFAS, PBDEs, dan MCCPs yang kadarnya melebihi batas aman yang ditetapkan Uni Eropa dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA).
“Sampel telur dari sekitar fasilitas pembakaran di Bantar Gebang menunjukkan adanya kontaminasi senyawa dioksin dan furan sangat tinggi. Ini mengindikasikan bahwa polutan telah masuk ke rantai makanan,” jelasnya.
Nindhita mengatakan, PLTSa di Indonesia belum mempunyai alat pemantauan emisi berkelanjutan yaitu Continuous Emission Monitoring System (CEMS).
“Harusnya, fokus pada sistem pengelolaan sampah terintegrasi mulai sumbernya, yaitu di rumah tangga dan rukun tetangga. Selain itu juga, menyiapkan regulasi dan infrastruktur pendukung,” jelasnya.

 1 month ago
49
1 month ago
49










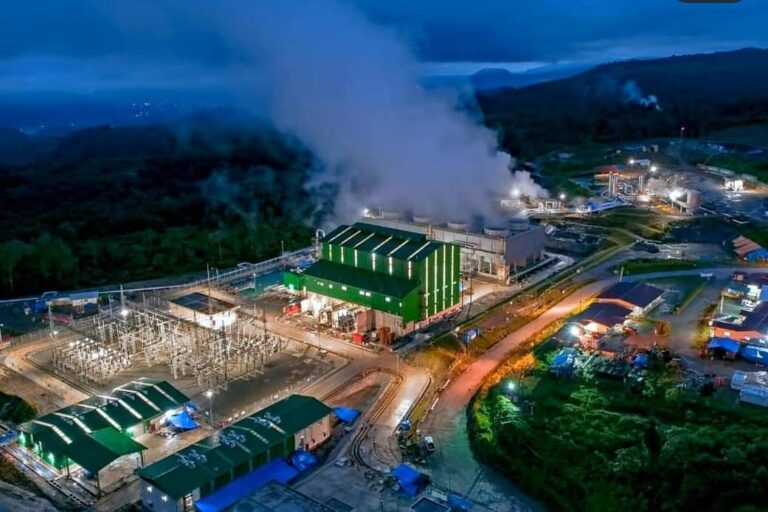




































![Ada Pembangkit Panas Bumi, Warga Rantau Dedap Tak Nikmati Listriknya [2]](https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2025/02/Kampung-Rantau-Dedap-tanpa-penerangan-listrik-PLN-meski-dekat-dengan-pembangkit-PLTP-SERD-1-768x512.jpg)

