- Masyarakat yang hidup di dekat industri pertambangan dan pabrik pengolahan nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) kehilangan tanah dan kebun. Ruang hidup mereka hilang untuk proyek hilirisasi nikel, pabrik untuk bikin bahan baku baterai kendaraan listrik.
- Infrastruktur raksasa ini berdiri persis di antara Desa Lelilef Sawai dan Woebulen di Weda Tengah dan Desa Gemaf di Weda Utara. Pembangunan fasilitas IWIP sudah menggunakan area lahan seluas 4.027,67 hektar atau 5.483 lapangan sepakbola.
- Faisal Ratuela, Direktur Eksekutif Walhi Maluku Utara mengatakan, kehadiran industri nikel, rakus lahan hingga mengkapling hutan tempat berburu sampai area-area perkebunan produktif warga di Weda Tengah dan Weda Utara. Alokasi ruang untuk industri begitu besar, menciptakan ketimpangan penguasaan hingga menghancurkan produksi dan konsumsi warga.
- Apa yang dihadapi warga di wilayah industri nikel khawatir memicu krisis lintas generasi. Mereka yang kehilangan lahan, kehilangan sungai, dan kehilangan akses terhadap pangan lokal, akan membawa pada krisis pangan.
Yulius Burnama mengenang masa manis yang berubah jadi pahit. Dia punya kebun kelapa, pala dan memelihara ratusan ribu ikan dalam kolam di tanah seluas dua hektar sejak 1995. Naas, awal 2019, tanpa izin maupun pemberitahuan, kebun dan kolam ikan itu tergusur dan kena timbun dengan urugan tanah.
Kini, Yulius pun tidak lagi berkebun. Dia banyak menghabiskan waktu di rumah. Lahan puluhan tahun yang jadi sumber hidup, pemerintah secara sepihak alokasikan untuk perluasan bandara udara dan pembangunan proyek kawasan industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Maluku Utara.
“Situ ada sekitar 600.000-an ikan nila, mujair, deng bandeng ada di tiga kolam itu, dong tutup samua, ikan-ikan mati samua. Disitu, di kobong saya tanam kalapa deng pala juga, ada coklat [kakao] sadiki, habis. Sampe sekarang tara bayar,” katanya.
Yulius tinggal di Desa Lelilef Sawai, Weda Tengah, Halmahera Tengah, berjarak sekitar 130 kilometer dari Sofifi, ibukota Maluku Utara. Rumah Yulius terletak di pesisir pantai, sementara kebun di sebelah kanan jalan utama trans Halmahera yang jadi bandara udara.
Lelilef Sawai jadi salah satu kampung terdampak proyek pembangunan kawasan industri nikel IWIP, perusahaan yang produksi bahan baku baterai kendaraan listrik. Kendaraan listrik sebagai kendaraan rendah emisi.
Infrastruktur proyek raksasa ini persis di antara Desa Lelilef Sawai dan Woebulen, Weda Tengah dan Desa Gemaf, Weda Utara.
Tercatat, nilai investasi untuk pembangunan awal IWIP pada 2018 senilai US$7,5 miliar. Setelah mengalami banyak perubahan kepemilikan, kini ada tiga investor asal Tiongkok yang jadi pengelola dan pemegang saham utama, yaitu, Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi.
Tsingshan pemegang saham 32% dan operator utama IWIP.
 PLTU batubara di Kawasan industri PT IWIP. Foto: Rabul Sawal/Mongabay Indonesia
PLTU batubara di Kawasan industri PT IWIP. Foto: Rabul Sawal/Mongabay IndonesiaDengan anggaran sebesar itu, terbangun fasilitas industri, pabrik pengolahan bijih nikel dan produksi bahan baku baterai, pembangkit listrik batubara, pelabuhan, bandara, hingga jalan dan infrastruktur transportasi. Fasilitas umum seperti klinik kesehatan, lapangan olahraga, perhotelan, dan area rekreasi juga ada menunjang industri nikel.
Saat ini, infrastruktur dan fasilitas kawasan industri IWIP sudah pakai lahan seluas 4.027,67 hektar, setara 5.483 lapangan sepakbola. Perusahaan masih akan menambah konsesi seluas 11.489,33 hektar, dengan target 15.517 hektar.
Sebelum seluas itu untuk kawasan industri, dulu wilayah ini ruang pangan warga. Tanah subur dengan beragam pangan lokal seperti sagu, dan pisang, sukun dan lain-lain.
Ada beberapa aliran sungai jernih, dengan hutan bakau dan bentang perbukitan.
Pemerintahan Joko Widodo menetapkan kawasan industri IWIP sebagai proyek strategis nasional (PSN), dan masuk objek vital nasional.
Lima tahun terakhir di periode keduanya, pemerintah ingin jadikan Indonesia menjadi pemain utama industri nikel di pasar global dengan mendorong program hilirisasi nikel. Program ini mereka kait-kaitkan dengan transisi energi, peralihan dari bahan bakar fosil untuk tekan emisi.
Pemerintahan Prabowo-Gibran melanjutkan warisan kebijakan hilirisasi ini. Akhir 2024, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkunjung ke kawasan industri IWIP.
Dalam waktu enam tahun sejak peresmian, sebagian besar warga kehilangan lahan perkebunan, tanaman pangan tercemar limbah, kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, hingga mesti menghadapi perubahan total pola hidup dan konsumsi tradisional.
 Buah pisang dari warga yang berjualan di sekitar kawasan IWIP. Buah-buah ini datang daeri daerah lain. Foto: Supriyadi S
Buah pisang dari warga yang berjualan di sekitar kawasan IWIP. Buah-buah ini datang daeri daerah lain. Foto: Supriyadi SPangan lokal hilang
Dina Loha pun alami seperti Yulius. Malam-malam setelah penggusuran pada 2019 itu, Dina Loha sering terbangun dari mimpi buruk. Kejadian di bawah alam sadarnya menampilkan kisah nyata menyedihkan: alat-alat berat meraung-raung, menumbangkan satu per satu kelapa dan tanaman pangan. Semua ludes. Di dalam mimpi dia seakan ikut terkubur ke tanah.
“Pas takage [saat kaget dari mimpi] saya langsung manangis skali. Saya inga skali saya pe kobong itu, [saya ingat sekali saya punya kebun itu],” cerita Dina.
Mimpi buruk itu tak jauh lebih kejam dari apa yang Dina rasakan sekarang. Dia kehilangan segalanya: lahan dua hektar lebih penuh ratusan tanaman kelapa, pala, kakao dan tanaman pangan lain.
Rumah Dina di Desa Gemaf, Weda Utara. Kebun Dina yang tergusur terletak di dekat jalan utama Trans Halmahera, menghubungkan antar desa dan kecamatan dari ibukota Halmahera Tengah. Di sebelah barat, berbatasan langsung dengan Sungai Ake Sake dan kebun warga Lelilef, sebelah utara dengan kebun warga Gemaf, hanya berjarak satu kilometer dari kampung.
Dia tidak ingat persis lokasi dan batas-batas kebun saat melewati area kawasan industri. Jalan dan sungai yang biasa jadi patokan batas kebun sudah hilang, alur sungai pindah dan tertutup dinding beton. Muara jadi tempat pembuangan limbah dari produksi pabrik, sisanya, terbentang fasilitas industri hingga ujung Desa Lelilef.
“Tong menderita biking kobong itu, tapi dong gusur rabu-rabu abis [Saya menderita bikin kebun itu, tapi mereka–perusahaan–gusur dengan cepat habis],” kata Dina.
Meski sudah enam tahun berlalu, tetapi detail-detail peristiwa itu masih terpatri kuat dalam ingatannya.
“Dong tara [mereka–perusahaan–tidak] bilang, datang-datang langsung gusur,” katanya.
“Dong gusur tapi tara langsung bayar, sampe berapa bulan, sekitar bulan anam [enam] baru [dibayar].”
Saat penggusuran terjadi, Dina sedang mengumpulkan buah kelapa di tepi Sungai Ake Sake. Dia tidak tahu, baru kaget saat mendengar suara bising menumbangkan satu per satu tanaman kelapa berbuah lebat, buahnya berhamburan sampai di tepi jalan.
Dina menangis histeris dan menghampiri alat-alat berat berusaha mencegah. Anak-anak perempuannya yang sedang memasak di rumah kebun, dan dua pemuda yang membantu Dina memanjat dan panen kelapa ikut menghadang.
Yulius, warga Lelilef juga alami hal serupa. Lelaki 74 tahun itu bahkan tak menikmati sepeserpun hasil kebun dan ikan-ikan di kolam setelah tergusur. Perusahaan sempat janji ganti rugi, tetapi berkali-kali mengadu ke pemerintah daerah, mendatangi kantor polisi, namun kompensasi tak kunjung ada.
“Saya datang lagi di perusahaan tanya proses [kompensasi] lahan deng kolam ikan sampe dimana karena sampe sekarang tidak dapat jawaban,” kata Yulius.
Pola konsumsi berubah, ingatan kolektif hilang
Perubahan lingkungan masif turut mengubah pola hidup di Lililef. Farida, perempuan 72 tahun di Lelilef Woebulen tunggang-langgang mengais hidup setelah kehilangan tanah dan kebun.
Dia tinggal dekat IWIP. Farida bilang, biaya konsumsi pangan sehari-hari sangat tinggi, sedang sumber penghasilan tidak ada.
Dulu, dia makan minum dari hasil kebun dengan tanam segala sumber pangan tanpa mengeluarkan ongkos sepeserpun.
“Sekarang samua beli,” kata Farida.”
“Pisang deng sagu me so bili, jadi kalu tarada doi, tong tara makan itu.”
Sumber-sumber pangan seperti pisang, singkong, sagu, kelapa buat santan, sampai rempah-rempah dapur seperti sayur, cabai dan tomat yang dulu cuma-cuma kini harus dengan uang di pasar.
Bahan-bahan pangan itu semua tersedia di pasar Lelilef hingga Gemaf, tetapi bukan berasal dari kebun warga. Semua dari pedagang luar Halmahera Tengah.
Sagu yang warga Lelilef konsumsi erasal dari Maba, Halmahera Timur. Pisang, singkong, rempah-rempah dapur hingga ikan, sebagian suplai dari daratan Obi, Tidore Kepulauan, bahkan Kota Ternate.
“Kalu tong mo makan sagu, musi tunggu orang Maba bawa datang, dong jual tong beli baru makan. Jadi, kalu dong datang [jualan] kong ada doi, tong beli banya-banya [untuk stok],” ujar Dina.
Tanpa kebun, Dina harus putar kepala mencari penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari selain berharap anak-anaknya yang bekerja di perusahaan. Ongkos makan-minum dan sekolah dua cucu bisa habis Rp150.000- Rp250.000 setiap hari. Belum termasuk ongkos bulanan.
Dina perkirakan, biaya membeli beras, membayar listrik, air bersih, dan kebutuhan di dalam rumah bisa lebih Rp 5 juta per bulan.
“Tong kase kaluar doi tara sangka-sangka so abis, doi Rp5 juta tu tara cukup, me samua serba bili. Baras 1 karung 25 kilo (gr) ni tara sampe satu bulan, baru dia pe harga saja Rp350.000. Bolom me aer, bayar lampu, ampong.”
Tradisi makan pinang tak banyak lagi di wilayah ini, karena sudah harus beli bukan hasil petik kebun.
Konsumsi pangan lokal juga demikian, mesti mereka dapatkan dengan uang dan tak lagi bisa tersaji saban hari di meja makan.
Dina kadang memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sedikit rempah-rempah seperti cabai dan tomat meski hanya tiga sampai empat tanaman agar tak selalu dia belanja di pasar. Dina tak mau kehilangan kebiasaan berkebun, meski sekadar pekerjaan sampingan, bukan lagi yang utama.
Meski tak semua warga di Gemaf kehilangan tanah seperti Dina, tetapi kebun-kebun tersisa sudah tidak diolah. Selain faktor usia, kebun-kebun tersisa sudah diukur dan ditawar perusahaan, sebagian sudah dibayar.
Fenias Nusu, misal, lelaki 80 tahun di Gemaf ini sebetulnya masih punya kebun, tetapi tenaga tua. Fenias tanam kelapa di sebelah utara Gemaf dekat jalan utama menuju Sagea, berjarak sekitar tiga kilometer dari rumahnya.
Awal Desember lalu, Fenias mengajak saya ke kebun itu dengan kendaraan motor. Dari jalan, dia menunjuk kebun berbatasan dengan sungai dan jalan koridor tambang batu gamping, yang menambang batu gamping di area Gemaf-Sagea.
Saat berjalan memasuki kebun, lelaki itu kebingungan mencari jalan. Rumput-rumput sudah setinggi di atas kepala orang dewasa. Pohon-pohon hampir melewati batang kelapa. Buah yang jatuh sudah bertunas dan sebagian tak terlihat. Kebun itu tak terurus.
“So tara biking kobong ini so ampir ampa tahun, so barumpu samua ni, [sudah tidak bikin kebun ini sudah hampir empat tahun, sudah berumput semua ini]” kata Fenias, tetua di Gemaf.
Perubahan pola konsumsi dan tradisi mengolah pangan lokal pun terkikis, terutama pada generasi yang kehilangan akses terhadap tanah dan kebun. Mereka juga berisiko kehilangan kosakata lokal.
“Anak-anak jaman skarang ni dong so tara makan-makan sagu, makan baras saja, tako nanti [kedepan] dong so tara tau bahalo sagu, deng samua ilang sudah.”
Mongabay berusaha mewawancarai IWIP. Surat konfirmasi Mongabay ajukan sejak 20 Januari 2025. Staf Humas IWIP menjawab akan diskusikan dengan internal tim dan manajemen. Mongabay tanyakan lagi, pada 4 Februari, jawaban masih menanti persetujuan atasan. Sampai tulisan ini terbit pun jawaban perusahaan belum ada.
 Kawasan industri PT IWIP. Foto: Rabul Sawal/Mongabay Indonesia
Kawasan industri PT IWIP. Foto: Rabul Sawal/Mongabay Indonesia***
Masyarakat yang hidup di sekitar IWIP merasakan kendaraan motor dan mobil lalu lalang setiap waktu. Pada pagi dan sore hari jelang petang, jalanan selalu padat saat pergantian jadwal kerja ketika para buruh pulang dan pergi bekerja. Macet bahkan terjadi begitu parah saat berkendara dari Lukolamo hingga memasuki kawasan industri.
Mobilitas dan pertambahan penduduk dari luar daerah makin banyak dan padat. Ada yang datang untuk bekerja, membuka warung makan, kos kosan dan penginapan, kedai kopi, toko bangunan, pakaian, rental kendaraan, bengkel, hingga toko-toko elektronik.
Bangunan-bangunan usaha ini berderet-deret sepanjang jalan utama dari Desa Lukolamo memasuki Lelilef Sawai dan Lelilef Woebulen di Weda Tengah hingga Gemaf dan Sagea-Kiya di Weda Utara. Sulit membedakan mana rumah warga atau indekos maupun penginapan saat memasuki kampung-kampung ini, kecuali orang yang sudah menetap lama.
Di wilayah ini, langit tidak cerah. Debu jalanan, knalpot kendaraan, aktivitas lalu lalang alat-alat berat perusahaan, sampai polusi pembangkit listrik batubara dari kawasan industri beraduk di udara.
Rumah, warung, dan toko-toko di dekat jalan mesti membersihkan debu setiap waktu, yang lain membiarkan debu menempel di dinding-dinding sampai dalam rumah.
Kalau musim hujan lain lagi ceritanya, jalanan becek dan sangat licin. Di badan jalan pada beberapa tempat yang tak teraspal, tanah terpental dan membentuk kolam-kolam kecil. Jangan coba-coba bawa motor dengan kecepatan di atas 60 kilometer per jam, bisa terseret jatuh.
Di sudut-sudut lorong kecil, di pekarangan rumah dan indekos, hingga pertokoan dan warung-warung, sampah berhamburan dimana-mana. Beberapa titik di tepi jalan, meski sudah tertulis larangan, banyak sampah berbau busuk menyengat, berisi popok bekas, sisa makanan sampai pembalut, hingga bekas botol kalengan dan plastik, menumpuk tak terurus.
Selama seminggu di Lelilef dan Gemaf Desember 2024, agak sulit melihat warga pergi ke kebun memanen kelapa dan pala, mengolah sagu, atau menggendong saloi memanen rempah-rempah sayur, cabe, tomat di kebun. Sebagian besar mereka telah tanah dan ruang hidup.
Begitu pula sumber air yang sebelumnya tersedia di alam seperti dari Sungai Kobe, Ake Sake, Ake Wosia, Ake Doma, dan beberapa mata air yang membentuk peradaban dan terbentang di alam Weda Tengah dan Weda Utara, kini mengenaskan. Sungai rusak parah tercemar limbah, dan keruh setiap waktu meski tak hujan.
Yulius dan Dina yang kehilangan kebun, juga tak punya sumber air lagi. Warga tidak bisa lagi mandi, mencuci, minum, atau bikin ritual baptis di aliran-aliran sungai.
“Sapa yang barani minum aer di sungai-sungai itu? Barani minum langsung tere,” ujar Yulius terkekeh. Tere berarti ketika seseorang terpapar racun dan langsung meninggal di tempat.
Ketika hujan, sungai-sungai ini berubah wujud jadi bencana. Banjir bandang pada bulan Juli 2024 dari luapan Sungai Kobe setinggi dua meter merendam beberapa permukiman–termasuk kampung Yulius di Lelilef. Juga memutus akses jalan utama Trans Weda-Waleh, hingga melumpuhkan aktivitas warga.
Ada belasan kali banjir. Sumber-sumber air ini, dari analisis Forest Watch Indonesia (FWI) mengalami perubahan drastis. Pembangunan kawasan industri IWIP di hilir dan aktivitas pertambangan di hulu, menyebabkan deforestasi masif, mengubah bentang alam, dan tutupan lahan.
Berdasarkan laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) terdapat 19 izin usaha pertambangan mengkapling wilayah hutan alam Halmahera Tengah. Empat izin melintasi batas administrasi antara Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Luas konsesi dari seluruh izin mencapai 95.736,56 hektar atau 42% dari total luas wilayah Halmahera Tengah.
Menurut laporan Climate Rights International (CRI), terdapat 5.331 hektar hutan tropis ditebang di dalam konsesi pertambangan nikel di Halmahera. Ia melepas sekitar 2 juta metrik ton gas rumah kaca, dan akan meningkat seiring permintaan logam nikel.
Aktivitas industri nikel itu mengakibatkan masyarakat kecil seperti Dina dan Yulius menghadapi ancaman serius mata pencaharian dan cara hidup tradisional mereka. Kini, mereka tak lagi menjalani kehidupan tradisional setelah kehilangan tanah dan kebun, kehilangan sumber air sungai, dan lingkungan jadi kotor.
Supriyadi Sudirman, aktivis lingkungan Save Sagea, mengatakan, kehidupan masyarakat di Halmahera Tengah sebelum perusahaan tambang dan pengelolaan, dari bertani, berburu, dan melaut. Sebagian besar perkampungan di daratan Halmahera berada di pesisir yang penuh tanaman pangan dan kekayaan biodiversitas laut.
“Sekarang banyak orang Lelilef sampe Sagea sudah tidak punya lahan perkebunan. Lahan-lahan perkebunan justru untuk aktivitas industri. Walaupun beberapa warga masih punya kebun, sudah tidak terurus sama sekali. “
Situasi ini , katanya, akan menyebabkan krisis pangan akut berkepanjangan ke depan.
Sementara generasi muda di Halmahera Tengah saat ini, katanya, tidak lagi tertarik bekerja sebagai petani kebun atau sektor pertanian. Sebagian besar mereka memilih sebagai pekerja tambang dan pabrik nikel IWIP.
Peralihan kerja terjadi sejak IWIP aktif beroperasi pada 2019. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dalam rentang waktu 2015-2023 sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan terjun bebas setelah lapangan usaha sektor industri ekstraktif masif.
Pada 2015, pertanian masih jadi unggulan di angka 26,71% dan melandai perlahan-lahan hingga puncaknya 2,11% pada 2023. Sebaliknya, sektor pertambangan dan pengolahan awalnya 15% dan 2,7% pada 2015 naik drastis jadi 32,23% dan 58,79% pada 2023.
Peningkatan sektor ekstraktif tak serta merta mengubah kehidupan ekonomi warga di Weda Tengah dan Weda Utara menjadi lebih baik. Sebaliknya, warga justru makin terhimpit memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Sebelumnya, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, sangat dominan menjadi penopang ekonomi Halmahera Tengah. Di sektor pertanian, terutama perkebunan rakyat, pala, kelapa, dan kakao bahkan menjadi komoditas unggulan sampai sekarang.
Secara produksi dan luasan lahan pertanian juga berkurang seiring pembukaan lahan untuk pertambangan. Berdasarkan data produksi perkebunan rakyat Dinas Pertanian Halmahera Tengah, hasil kelapa, pala, dan kakao terlihat melandai pelan-pelan.
Pada 2019, kelapa, pala, dan kakao, masing-masing 8.097,0 ton, 1.807,0 ton, dan 407,0 ton. Selain pala, mulai menurun pada 2023 masing-masing 7.131,5 ton, 1.857,1 ton, dan 325,0 ton.
 Sampah berserakan sembarangan di kampung-kampung sekitar kawasan PT IWIP. Foto: Rabul Sawal/Mongabay Indonesia
Sampah berserakan sembarangan di kampung-kampung sekitar kawasan PT IWIP. Foto: Rabul Sawal/Mongabay IndonesiaYusmar Ohorella, Kepala Dinas Pertanian Halmahera Tengah mengatakan, pala yang meningkat bukan dari Weda Tengah dan Weda Utara. Pala masih unggulan di Patani, berjarak sekitar 60 kilometer dari kawasan industri IWIP.
Sementara hasil kelapa sebagian dari Fritu dan Waleh, di ujung Weda Utara menuju Patani. Di daerah-daerah ini, sebagian besar kebun tidak terjamah pertambangan nikel.
Wilayah yang produksi perkebunan mulai menurun, kata Yusmar, terjadi dari Sagea-Kiya dan Gemaf di Weda Utara hingga Lelilef Woebulen dan Lelilef Sawai. Kebun masyarakat, katanya, sudah mereka jual ke perusahaan.
Menurut Yusmar, di Lelilef sampai Sagea sudah bukan masyarakat pertanian tetapi masyarakat industri. Sebagian besar pasokan pangan datang dari luar seperti Tobelo, Halmahera Utara, wilayah Buli-Maba di Halmahera Timur, Oba di Tidore Kepulauan. Sebagian lagi dari wilayah-wilayah yang masih punya lahan pertanian produktif di Halmahera Tengah.
Faisal Ratuela, Direktur Eksekutif Walhi Maluku Utara khawatir dengan pasokan pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah Lelilef hingga Sagea dari luar daerah. Wilayah ini, sebelum kehadiran perusahaan kaya sumber pangan seperti sagu.
Kehadiran industri nikel, kata Faisal, rakus lahan hingga mengkapling hutan tempat berburu sampai area-area perkebunan produktif warga di Weda Tengah dan Weda Utara. Alokasi ruang untuk industri begitu besar, katanya, menciptakan ketimpangan penguasaan hingga menghancurkan produksi dan konsumsi warga.
“Sehingga warga seperti di Lelilef Sawai, Lelilef Woebulen, Gemaf di titik jantung produksi nikel menghadapi ancaman serius pangan mereka. Mereka tidak lagi mengonumsi makanan seperti sagu, atau pangan batatas, kasbi, dan lain-lainnya,” katanya.
Faisal khawatir, warga di wilayah industri nikel yang jadi proyek strategis nasional ini bakal memicu krisis lintas generasi. Mereka yang kehilangan lahan, sungai tempat peradaban, udara bersih, dan akses terhadap pangan lokal, berujung krisis pangan. Semua pangan datang dari luar.
Pemerintah, katanya, mesti mengevaluasi lagi izin-izin tambang dan operasi pabrik di Halmahera Tengah, mengingat kerusakan sudah sangat parah.
“Kalau tidak evaluasi proyek PSN ini, warga Halmahera, terutama di daerah industri nikel seperti di Lelilef dan sekitar, bakal makin menderita dan kehilangan seluruh akses terhadap pangan dan ruang hidup mereka.”
*Laporan ini merupakan hasil liputan fellowship transisi energi dari Remotivi dan WRI Indonesia.
 Penampakan kawasan industri PT IWIP dari kejauhan. Foto: Supriyadi S
Penampakan kawasan industri PT IWIP dari kejauhan. Foto: Supriyadi S*******
Menyoal Pengembangan Baterai Nikel bagi Lingkungan Hidup dan Sosial

 1 month ago
69
1 month ago
69


![Ironi Penguatan Pangan Kala Lahan Petani Terus Tergusur [2]](https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2025/04/desa-Iwul-4-768x512.jpg)





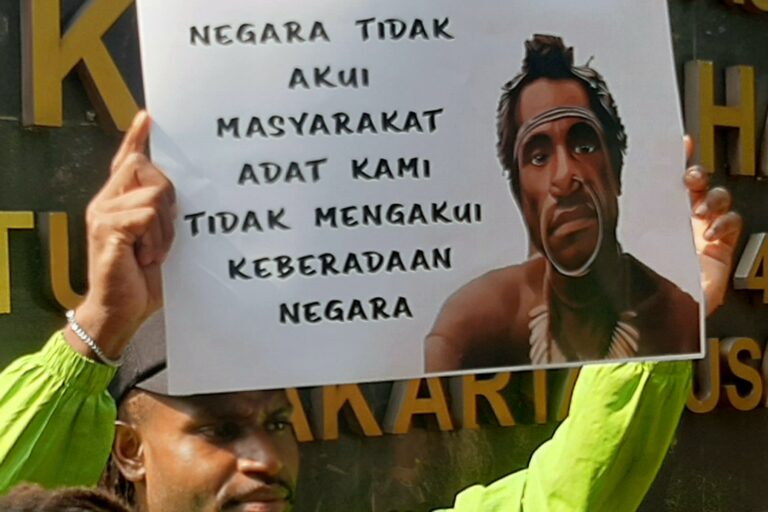




![Protes Penggusuran, Warga Desa Iwul Tanam Pohon [1]](https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2025/04/Foto-dari-Achmad-Rizki-Muazam-3-768x512.jpg)































